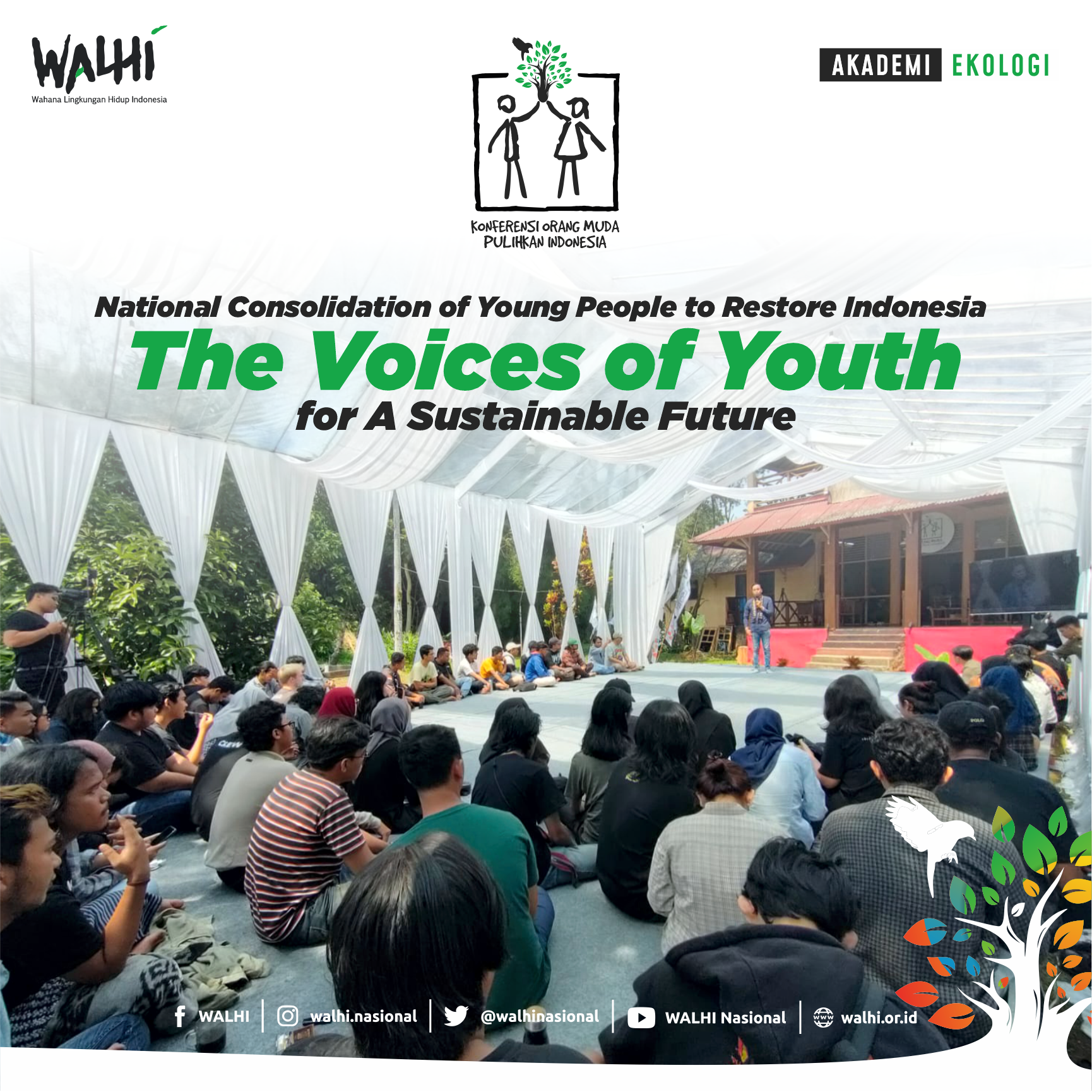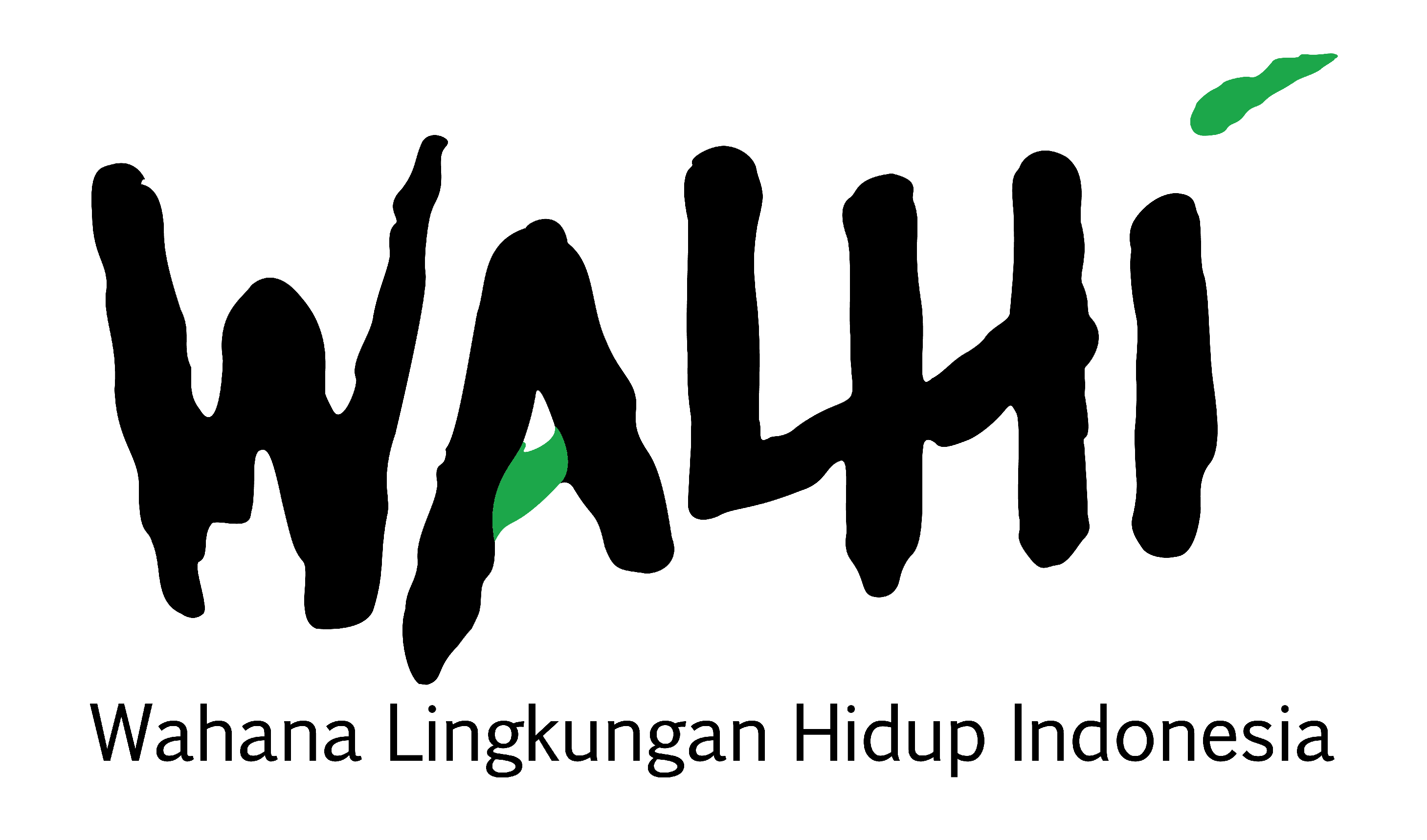Di tengah krisis pandemi COVID-19, Pemerintah dan DPR masih saja memaksakan pembahasan beberapa regulasi strategis seperti RUU CILAKA (cipta kerja), RUU MINERBA, RKUHP, dan beberapa regulasi lainnya.
Kami menilai tidak etis memaksakan proses pembahasan diatas, atas pertimbangan:
Pertama, publik di tengah krisis saat ini memberikan fokusnya pada penanganan COVID-19, sehingga proses partisipasi publik pasti memiliki keterbatasan. Pada konteks ini bukan hanya publik, tetapi juga para pihak terkait termasuk pemerintah daerah. kami meminta DPR menghentikan segala pembahasan legislasi di Parlemen dan fokus pada penanganan pandemik. Jika legislasi tersebut tidak berkaitan dengan penanganan COVID-19 harus dihentikan apalagi membahas Omnibus Law itu sama saja menikam rakyat dari belakang.
Kedua, Kami menilai DPR dan Pemerintah jika memaksakan pembahasan-pembahasan regulasi yang tidak terkait langsung dengan penanganan COVID-19, maka pada prinsipnya telah gagal menentukan prioritas.
Ketiga, semua regulasi yang dipaksakan ditengah situasi pandemi saat ini, maka akan kehilangan legitimasinya.
Bagi publik setidaknya upaya-upaya diatas telah melukai rasa keadilan publik, setidaknya sudah 3 kali momentum dimana negara memberlakukan standard ganda, antara terhadap rakyat dan elit:
(1) Saat DPR mengumumkan rapid test COVID-19 untuk anggota dewan dan keluarganya, dimana pada saat itu garda terdepan, kelompok rentan belum memperoleh kepastian.
(2) Saat pembukaan sidang DPR, saat publik diminta tidak berkumpul, bahkan beberapa pembubaran dilakukan dengan tidak layak, justru contoh yang buruk diberikan anggota dewan.
(3) Saat pembahasan omnibus law dan regulasi lainnya ini tetap dipaksakan.
Salam
Narahubung:
Wahyu (WALHI)
Asep (greenpeace)
Raynaldo (ICEL)
------------
Catatan untuk Editor dan Redaksi terkait Omnibus Law
Pertama, direduksinya norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Dihapusnya unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dikhawatirkan mengaburkan pengoperasian ketentuan ini. Belum lagi ketentuan Pasal 49 UU Kehutanan diubah total, tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi, di RUU “Cilaka” diubah sekadar bertanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Pada Judicial Review yang diajukan dua asosiasi pengusahan tersebut di tahun 2017 juga diminta penghapusan Pasal 99 UU PPLH. Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan dua ketentuan yang dipergunakan untuk menjerat korporasi-korporasi pembakar hutan dan lahan. Di RUU Cipta Lapangan Kerja, tidak sekedar Pasal 99 yang dilemahkan, termasuk Pasal 98. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu dilakukan melalui skema administrasi. Bahkan ketentuan pidana sangat sulit dioperasikan kepada korporasi karena tidak ada sanksi denda. Seharusnya perumus RUU harus konsisten membedakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.
Hal diatas sudah dapat diduga dengan ditunjuknya Ketua Umum Kadin sebagai ketua Satuan Tugas Bersama (Task Force) Naskah Akademik dan Draft RUU. Terlebih ada bukti beberapa ketentuan yang direduksi adalah ketentuan pertanggungjawaban hukum yang pernah dicoba diuji oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi. Pada Pada 19 Mei 2017 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melalui kuasanya Refly Harun dkk menguji Pasal 69 ayat (2), Pasal 88 & Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Permohonan Pengujjian Undang-Undang (Nomor Perkara: 25/PUU-XV/2017). Pada sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi Palguna menyampaikan: “di dalam wacana hukum lingkungan, kita sering menyebut ada istilah eco terrorism, dan sebagainya. Itu yang salah satu juga pendorong makin memperkuat diterima universalitas prinsip strict liability ini. dan kita juga tahu prinsip strict liability yang bisa membebaskan kan apa yang disebut sebagai Act of God, force majeure, dan sebagainya itu kita sudah semua tahu.”
Kedua, ini adalah hal yang paling konyol!, ruang partisipasi publik dihapus. Hak partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah dihapus. RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
WALHI dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja, persoalan mendasarnya bukan hanya karena ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. RUU ini secara substansi dan sejak awal memang untuk melayani kepentingan investasi.
Janji Jokowi untuk berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup hanya bualan. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan akan memperparah kondisi krisis apabila RUU ini dipaksa untuk disahkan. DIBAHAS SAJA TIDAK PANTAS !