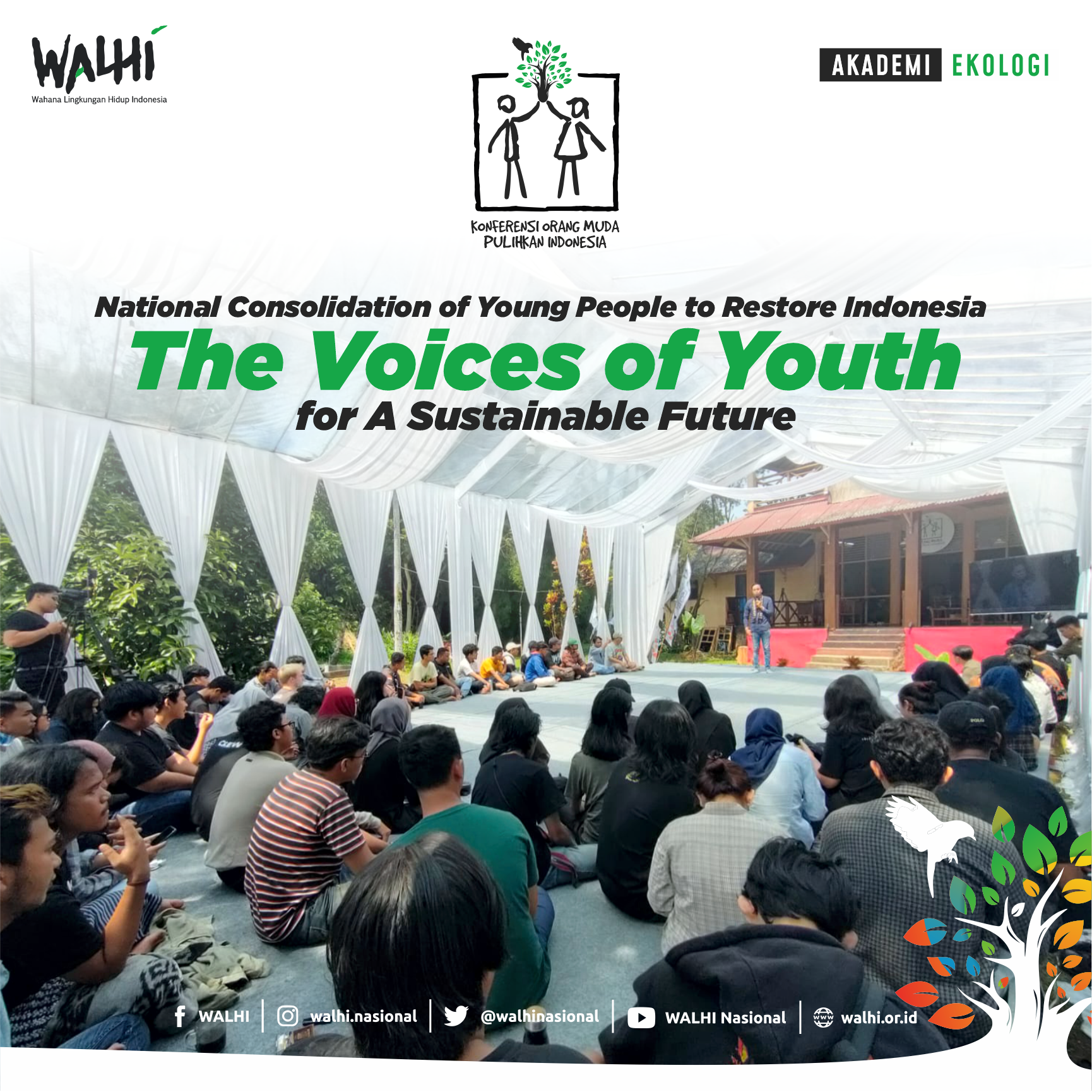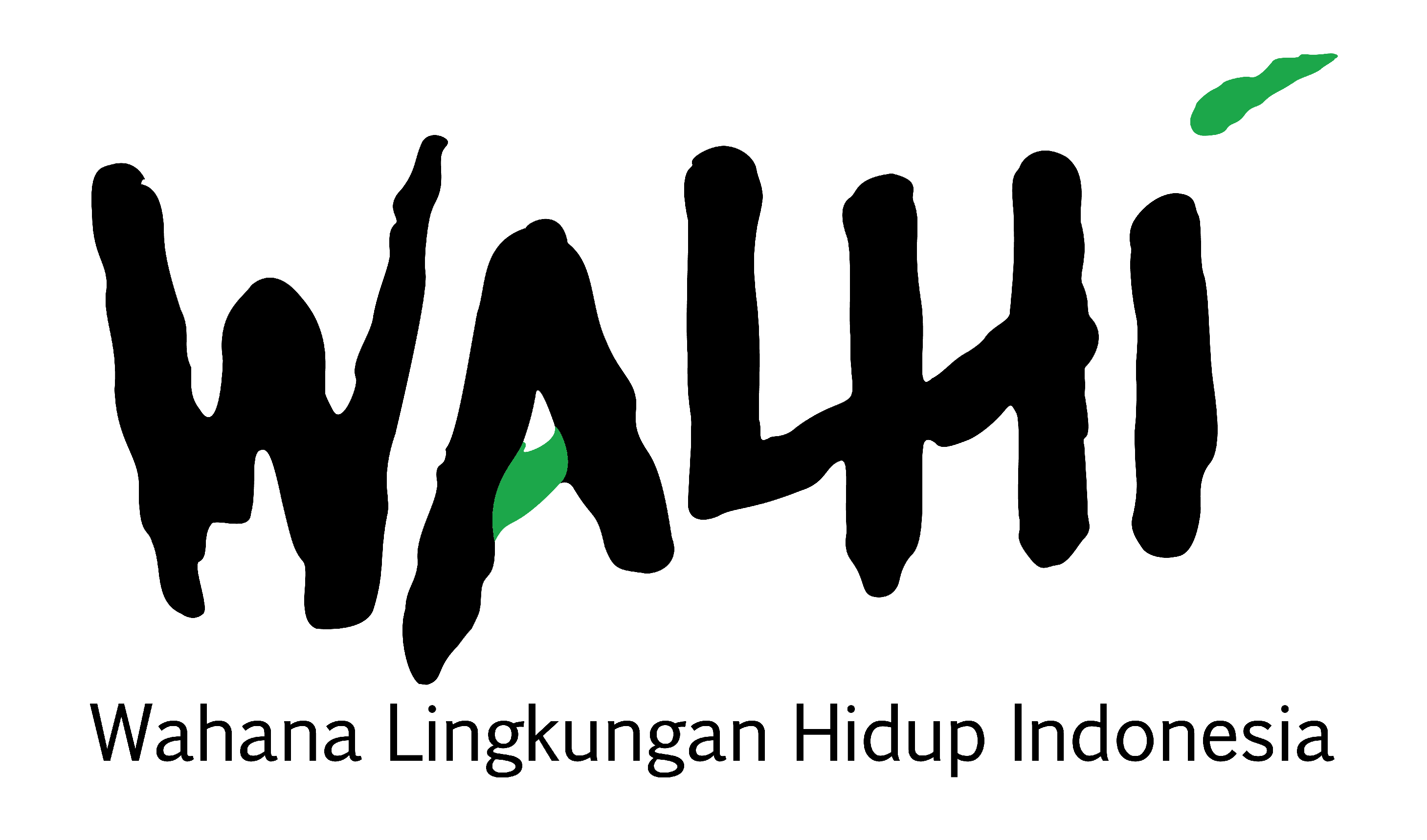Kertas Posisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Pendahuluan Sejak tahun 2000, WALHI menyuarakan desakan moratorium atau jeda tebang bagi industri-industri penebangan kayu, yang didorong oleh semakin meningkatnya laju deforestasi yang berkumulasi pada krisis lingkungan hidup di Indonesia. Desakan ini juga disampaikan kepada negara-negara pemberi pinjaman kepada Indonesia, untuk mendukung upaya moratorium ini.[1] Pada saat itu, Menteri Lingkungan Hidup beberapa Pemerintah Daerah sudah menyetujui tawaran agenda moratorium, namun rezim birokrasi di Kementerian Kehutanan kala itu menjadi tembok penghalang yang begitu kokoh, bahkan sampai di periode pemerintahan Megawati. Baru pada tahun 2010, Pemerintahan SBY mengeluarkan kebijakan moratorium selama dua tahun pemberian izin baru di hutan primer dan gambut yang tertuang dalam Inpres No 10/2011. Pada tahun 2013, SBY kembali memperpanjang kebijakan moratorium melalu Inpres No. 6 tahun 2013. Pemerintah kembali melanjutkan penundaan pemberian izin baru di hutan alam dan lahan gambut di kawasan hutan alam, hutan produksi dan konservasi, kembali hingga dua tahun berikutnya (Mei 2015). Dari pengalaman selama dua kali masa perpanjangan Inpres moratorium di masa pemerintahan SBY, WALHI menilai tidak ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola sumber daya alam kita, khususnya di sektor kehutanan.
Bahkan kebijakan moratorium dipastikan gagal mencapai tujuan utama dari moratorium. Kebijakan dan regulasi terus dikeluarkan secara tumpang tindih, review perizinan tidak berjalan dan bahkan pelanggaran hukum terus terjadi. Pada periode Inpres pertama, WALHI bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global telah mengajukan usulan bagi pemerintah yang tertuang dalam platform bersama moratorium berbasis capaian. Di dalam platform tersebut, juga ditawarkan definisi moratorium yakni penghentian untuk jangka waktu tertentu dari aktivitas penebangan dan konversi hutan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen. Dengan tujuan untuk mencari cara terbaik untuk keluar dari berbagai dampak negatif dari industri di sektor kehutanan, langkah awal melakukan restorasi ekosistem hutan dan rawa gambut, perbaikan kinerja tata kelola, penegakan dan kepastian hukum, serta menghentikan deforestasi. Pada masa jelang berakhirnya Inpres No. 6/2013, WALHI dan Koalisi mengusulkan tawaran memperkuat kebijakan moratorium dari mulai aturan hukumnya, hingga langkah-langkah untuk implementasi moratorium ini, berbasiskan evaluasi atas kebijakan moratorium di masa pemerintahan sebelumnya.
Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan kebijakan melanjutkan moratorium melalui Inpres No. 8 tahun 2015 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. Inpres ini juga bertujuan menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dalam kerangka menurunkan emisi dari deforestasi serta degradasi hutan. Presiden Jokowi memang berkomitmen menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut, tapi lagi-lagi kebijakan moratorium juga dapat dikatakan belum memiliki kekuatan. Selain mendapatkan apresiasi, kebijakan Presiden ini juga mendapatkan sorotan kritik dari banyak pihak, utamanya karena Inpres ini hanya memiliki semangat memperpanjang moratorium untuk dua tahun (lagi), sementara secara substansi masih jauh dari menjawab problem pokok dan struktural dari carut marutnya pengelolaan sumber daya alam kita. Sejak awal keluarnya Inpres ini, WALHI mengkhawatirkan kebijakan ini amenemui nasib yang sama seperti kebijakan sebelumnya. Hanya menjadi secarik kertas, tidak memiliki kekuatan hukum dan bahkan tidak bersifat mandatory bagi Kementerian/Lembaga negara lainnya, termasuk Pemerintah Daerah, yang kini kewenangannya kembali bertumpu pada Provinsi sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014. 3 (tiga) bulan paska Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Moratorium, peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi. Data WALHI menyebutkan titik api sebagian besar berada di wilayah konsesi perusahaan dan yang ironinya titik api juga ditemukan di area peta indikatif penundaan izin (PIPIB). Artinya, Presiden Jokowi tidak menggunakan kesempatan penyelamatan hutan dan lahan gambut di Indonesia yang berakibat pada kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat.
Kala itu, Presiden memilih melewatkan kesempatan membuat gebrakan penyelamatan lingkungan hidup, hutan alam dan ekosistem rawa gambut dengan memperkuat kebijakan moratorium. Inpres No. 8 Tahun 2015 akan berakhir. Sama seperti dua tahun sebelumnya, kita masih menanti keputusan Presiden, apakah kebijakan moratorium akan segera dikeluarkan. Terlebih kita tahu, bahwa moratorium terhadap perizinan perkebunan sawit telah disiapkan sejak tahun 2016, sayangnya sejauh ini publik belum mengetahui sampai dimana prosesnya, di tengah berbagai tantangan dan dinamika ekonomi politik yang berkembang di dalam dan luar negeri.
Evaluasi Kebijakan Moratorium  Sebelum kita bicara pada urgensi adanya kebijakan moratorium, ada baiknya kita melihat kembali implementasi kebijakan ini dari waktu ke waktu, hingga perpanjangan moratorium untuk ketiga kalinya sejak tahun 2011 dengan Inpres No. 10/2011, Inpres No. 6/2013 hingga Inpres No. 8/2015. Melihat kembali latar belakang dan urgensi mengapa kebijakan moratorium ini sangat penting dan tujuan yang hendak kita capai melalui kebijakan ini, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden ini tidak berarti, bahkan bagi institusi pemerintahan sendiri, terlebih bagi korporasi yang menjadi aktor utama selama ini dalam cerita penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang begitu besar. Dalam dokumen rencana kehutanan tingkat nasional 2011 – 2030 (RKTN 2011 – 2030) yang ditetapkan pada 8 Juni 2011, rencana kehutanan yang merupakan mandat UU 41 Tahun 2009 Pasal 20, yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat untuk arahan makro indikatif sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan, rencana investasi dan rencana kerja usaha yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan yang di atur dalam PP No. 44 Tahun 2004 untuk memunculkan arahan spasial makro. Dalam RKTN terbagi 6 kelas arahan makro.
Sebelum kita bicara pada urgensi adanya kebijakan moratorium, ada baiknya kita melihat kembali implementasi kebijakan ini dari waktu ke waktu, hingga perpanjangan moratorium untuk ketiga kalinya sejak tahun 2011 dengan Inpres No. 10/2011, Inpres No. 6/2013 hingga Inpres No. 8/2015. Melihat kembali latar belakang dan urgensi mengapa kebijakan moratorium ini sangat penting dan tujuan yang hendak kita capai melalui kebijakan ini, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden ini tidak berarti, bahkan bagi institusi pemerintahan sendiri, terlebih bagi korporasi yang menjadi aktor utama selama ini dalam cerita penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang begitu besar. Dalam dokumen rencana kehutanan tingkat nasional 2011 – 2030 (RKTN 2011 – 2030) yang ditetapkan pada 8 Juni 2011, rencana kehutanan yang merupakan mandat UU 41 Tahun 2009 Pasal 20, yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat untuk arahan makro indikatif sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan, rencana investasi dan rencana kerja usaha yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan yang di atur dalam PP No. 44 Tahun 2004 untuk memunculkan arahan spasial makro. Dalam RKTN terbagi 6 kelas arahan makro.
| NO | ARAHAN RKTN | LUAS (HA) |
| 1 | Kawasan Untuk Konservasi | 23.200.000 |
| 2 | Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam Dan Lahan Gambut | 28.400.000 |
| 3 | Kawasan Untuk Rehabilitasi | 13.530.000 |
| 4 | Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar | 54.520.000 |
| 5 | Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil | 6.970.000 |
| 6 | Kawasan Untuk Non Kehutanan | 4.060.000 |
Jika mengacu pada RKTN, untuk mengisi ruang Inpres No. 10 Tahun 2011 yang terbit pada 20 Mei 2011 dan kemudian secara spasial ditetapkan dengan Kepmenhut Nomor : SK.323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB) pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukkan kawasan hutan dan areal penggunaan lain yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2011 dengan Luas 69.144.073 hektar. Dari analisis spasial yang WALHI lakukan terhadap data arahan RKTN dan PIPIB ditemukan alokasi dan luasan PIPIB, sebagian besar berasal dari kawasan perlindungan hutan alam dan lahan gambut, kawasan konservasi dan rehabilitasi. Ini membuktikan bahwa penataan, rasionalisasi dan pembatasan perizinan di kawasan hutan menjadi tidak signifikan dalam tata kelola hutan alam dan lahan yang gambut yang terdapat dapat Inpres moratorium.
| NO | ARAHAN RKTN 2011 - 2030 | LUAS (Ha) |
| 1 | Kawasan Untuk Konservasi | 8.700.715,27 |
| 2 | Kawasan Untuk Non Kehutanan | 24.239,23 |
| 3 | Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar | 10.065.445,04 |
| 4 | Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil | 2.142.368,85 |
| 5 | Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam Dan Lahan Gambut | 25.772.006,38 |
| 6 | Kawasan Untuk Rehabilitasi | 7.277.541,47 |
| 7 | Non Kawasan Hutan | 4.461.757 |
| Total | 69.144.073 |
Fakta penguasaan perizinan untuk korporasi dikawasan hutan dan Non Kawasan Hutan hingga akhir tahun 2016.
| Sektor | Jenis Izin | Luas (Ha) |
| Kehutanan | IUPHHK-HA | 19.476.140 |
| Kehutanan | IUPHHK-HT | 10.890.144 |
| Kehutanan | IPPKH Tambang | 408.005,58 |
| Kehutanan | IPPKH Non Tambang | 20.315,79 |
| Perkebunan | Izin Perkebunan Sawit | 11.672.861 |
| Pertambangan | IUP | 34.727.338 |
| Pertambangan | Kontrak Karya | 2.210.698 |
| Pertambangan | PKP2B | 1.956.194 |
| Total | 81.361.696.37 |
Kebijakan moratorium hendaknya dilihat dalam upaya pembenahan dan perbaikan pada tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang membutuhkan waktu yang tidaklah sebentar. Sehingga 2 (dua) tahun kebijakan ini berlaku, tidak akan menghasilkan perbaikan apapun. Waktu pemulihan jasa layanan alam tidak sebanding dengan laju kerusakan yang dihasilkan dari sebuah perizinan.  Bahwa carut marut tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan telah melahirkan begitu banyak masalah, selain deforestasi, kebakaran dan konflik tenurial yang begitu tinggi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sehingag kebijakan moratorium berbasis capaian dengan indikator yang terukur sekali lagi menjadi maha penting. Ini belum ditambah dengan persoalan penyelesaian tata batas kawasan hutan, sinkronisasi berbagai peraturan dan regulasi turunannya dan yang tidak kalah mendesaknya melihat kembali perizinan yang telah dikeluarkan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran perundang-undangan dan regulasi lainnya, termasuk korporasi yang di dalam wilayah konsesinya ditemukan titik api. Dari kajian yang dilakukan oleh WALHI bersama dengan Kemitraan di 4 propinsi di Indonesia yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah pada tahun 2015, ditemukan berbagai persoalan dalam implementasi kebijakan moratorium.
Bahwa carut marut tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan telah melahirkan begitu banyak masalah, selain deforestasi, kebakaran dan konflik tenurial yang begitu tinggi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sehingag kebijakan moratorium berbasis capaian dengan indikator yang terukur sekali lagi menjadi maha penting. Ini belum ditambah dengan persoalan penyelesaian tata batas kawasan hutan, sinkronisasi berbagai peraturan dan regulasi turunannya dan yang tidak kalah mendesaknya melihat kembali perizinan yang telah dikeluarkan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran perundang-undangan dan regulasi lainnya, termasuk korporasi yang di dalam wilayah konsesinya ditemukan titik api. Dari kajian yang dilakukan oleh WALHI bersama dengan Kemitraan di 4 propinsi di Indonesia yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah pada tahun 2015, ditemukan berbagai persoalan dalam implementasi kebijakan moratorium.
Dari empat propinsi ini, luasan area yang dimoratorium terus mengalami pengurangan, pemberian izin tetap berlangsung dan bahkan nyaris sempurna modus operandinya jelang pilkada. Pemutihan peta dan rezim keterlanjuran menjadi argumentasi pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dari temuan implementasi kebijakan moratorium sebelumnya ditawarkan berbagai solusi. Di antaranya kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut bukan dibatasi waktu dua tahun per dua tahun, melainkan berbasis capaian dengan indikator yang dapat terukur, antara lain penurunan kebakaran hutan dan lahan. Sejak awal sudah diingatkan bahwa selain berbasis capaian yang jelas, inpres yang kuat juga harus dibarengi upaya penegakan hukum dan review perizinan, khususnya terhadap perusahaan yang di wilayah konsesinya ada titik api, bahkan secara berulang. Lalu bagaimana dengan implementasi kebijakan Inpres 8/2015 di masa pemerintahan saat ini? Sejak diterbitkan, WALHI memberikan catatan penting atas Inpres yang dikeluarkan, antara lain tentang pasal-pasal pengecualian pada izin prinsip yang telah dikeluarkan, yang berisiko bagi hutan alam dan lahan gambut yang tetap terancam dari deforestasi dan degradasi. Pengecualian lainnya adalah lahan untuk padi dan tebu, yang menandakan bahwa Inpres moratorium ini tetap berorientasi pada komoditas yang berkembang di pasar.
Pengecualian ini kemudian pada akhirnya mendorong beberapa wilayah kemudian menjadi sasaran lahan bisnis perkebunan tebu dan padi skala besar, selain perkebunan sawit. Inilah yang kemudian menyumbang angka deforestasi di Papua. Sedikitnya, Persetujuan prinsip IUP Perkebunan ada 130.324 hektar di tahun 2015 dan 29.886 hektar persetujuan prinsip IUP perkebunan pada tahun 2016. Dengan atas nama kedaulatan energi dan pangan, pemerintah memberikan kelonggaran atau pengecualian bagi industri. Selain Papua, investasi industri tebu menyasar provinsi NTT dan Maluku. Poin pengecualian bagi perpanjangan izin pemanfaatan hutan, mengisyaratkan pemerintah tak akan menggunakan masa moratorium sebagai momentum perbaikan tata kelola dan pemulihan fungsi serta daya dukung lingkungan. Dayang dukung lingkungan menderita karena beban perizinan yang overload. Karenanya, tidak mungkin ada pemulihan lingkungan, jika izin tidak direview oleh pemerintah. Instruksi yang diberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, untuk mengkonsolidasi peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) dalam peta tata ruang merupakan logika terbalik moratorium itu sendiri. Proses perencanaan tata ruang di daerah marak ditungangi pengusaha untuk mengubah kawasan hutan menjadi areal perkebunan dan tambang dengan pengusulan review kawasan hutan. Sampai Agustus 2014 terjadi pelepasan kawasan hutan hingga 7,8 juta hektar, karena tuntutan penyesuaian ke dalam tata ruang daerah. Selama masa moratoium, total penerbitan izin mencapai 11.362.981 hektar; pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 1.677.217,52 Hektar, kebun kayu melalui skema perizinan IUPHHK-HT hingga 1.725.467 hektar, izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 193.896 hektar, pelepasan kawasan hutan untuk pemenuhan permintaan wilayah administrasi daerah dalam bentuk Area Peruntukan Lain (APL) seluas 7,7 Juta hektar di 20 Provinsi.  Selama enam tahun pelaksanaan moratorium, luas areal hutan alam primer dan lahan gambut yang dimoratorium cenderung mengalami penurunan dari 69,14 juta hektar pada Juni 2011 menjadi 66,44 juta hektar di November 2016. Meski diakui dalam dua tahun terakhir luas areal moratorium mengalami peningkatan sebesar 2,42 juta hektar. Selama masa moratorium, Pemerintah juga telah melepaskan kawasan hutan secara parsial untuk perkebunan seluas 1.677.217 hektar, dengan rincian 944.071 hektar pada masa moratorium 2011-2013, seluas 645.005 hektar pada masa moratorium 2013-2015, dan terus terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan pada masa moratorium 2015-2017 meski angkanya lebih kecil yakni 88.140 hektar.
Selama enam tahun pelaksanaan moratorium, luas areal hutan alam primer dan lahan gambut yang dimoratorium cenderung mengalami penurunan dari 69,14 juta hektar pada Juni 2011 menjadi 66,44 juta hektar di November 2016. Meski diakui dalam dua tahun terakhir luas areal moratorium mengalami peningkatan sebesar 2,42 juta hektar. Selama masa moratorium, Pemerintah juga telah melepaskan kawasan hutan secara parsial untuk perkebunan seluas 1.677.217 hektar, dengan rincian 944.071 hektar pada masa moratorium 2011-2013, seluas 645.005 hektar pada masa moratorium 2013-2015, dan terus terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan pada masa moratorium 2015-2017 meski angkanya lebih kecil yakni 88.140 hektar.  Titik api juga berada di area moratorium, seperti yang ditemukan, antara lain, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Titik api juga berada di area moratorium, seperti yang ditemukan, antara lain, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Temuan titik api di area moratorium bisa menarik kita pada kesimpulan bahwa ini modus agar kawasan tersebut ditetapkan sebagai lahan kritis dan kemudian bisa diberikan sebagai lokasi konsesi. Apalagi, Inpres No 8/2015 masih sangat permisif, revisi dibuka ruangnya perenam bulan. WALHI menilai, selama enam tahun masa moratorium, tujuan utama dari kebijakan moratorium belum berhasil, pembenahan tata kelola sumber daya alam khususnya di sektor kehutanan belum terjadi. Komitmen dan Tantangan bagi Presiden Tantangan yang lain, kita tahu bahwa paska kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015, dan juga terjadi pada tahun 2016 meskipun dengan intensitas yang lebih rendah di tahun sebelumnya. Dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, pemerintah memandang perlu membentuk Badan yang akan melaksanakan kegiatan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) dan PP No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut seperti tidak memiliki kekuatan apa-apa dibandingkan dengan kekuasaan korporasi dengan atas nama keberlanjutan investasi. Di Kalimantan Barat misalnya, ada 860.011,811 hektar konsesi sawit di lahan gambut dengan 153 entitas korporasi di dalamnya. Dan IUP HKK-HT di gambut seluas 472.428,86 hektar. Yang ironi, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Sumsel menyatakan keberatan dengan PP 57/2016. Keberatan dari Gubernur Kalbar dan Sumsel ini menunjukkan upaya ketidakpatuhan mereka terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri dan bertentangan dengan komitmen Presiden dalam upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem rawa gambut, dengan alasan investasi dan sudah adanya konsesi perusahaan di sana.
Rezim keterlanjuran terus melegitimasi pengrusakan ekosistem rawa gambut oleh pemerintah. Pada jalan yang lain, korporasi telah masuk melalui parlemen untuk mendorong lahirnya UU Perkelapasawitan, yang saat ini pembahasannya terus digenjot oleh parlemen. Artinya, Inpres Presiden selama ini tidak dianggap sama sekali oleh anggota parlemen, pun partai politiknya konon mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Di tengah tantangan yang begitu besar, Presiden juga memiliki komitmen pemerataan ekonomi, khususnya kepada rakyat kecil melalui agenda reforma agraria dan perhutanan sosial untuk menjawab ketimpangan penguasaan dan pengelolaan struktur agraria. Karenanya, wilayah-wilayah yang potensial atau menjadi tanah objek reforma agraria (Tora) 9 juta hektar dan 12,7 juta hektar hutan dikeluarkan dalam PIPIB. Hal yang lainnya, tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial dapat diambil dari lahan-lahan industri yang perizinannya melanggar regulasi dan perundangan-undangan dan atau terdapat konflik. Tantangan ini tentu diharapkan dapat menjadi pelecut bahwa keberanian dibutuhkan dari seorang Presiden untuk secara sistematis dan struktural mengambil pilihan penting dan mendesak dengan memperkuat kebijakan moratorium, paska berakhirnya Inpres No. 8/2015 ini.
Penutup dan Rekomendasi Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 menegaskan bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Terlebih, dalam putusan gugatan Citizen Lawsuit di Kalimantan Tengah memerintahkan kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan dan penegakan hukum bagi perusahaan yang membakar. Putusan pengadilan ini dapat menjadi pijakan hukum bagi pemerintah dan momentum akan berakhirnya Inpres No. 8/2015 ini, dan memperkuat basis hukum kebijakan moratorium baru, setidaknya setingkat Peraturan Presiden (Perpres) yang bersifat lebih mengikat institusi negara baik di pusat maupun daerah, untuk semua sektor (perkebunan sawit, HPH, HTI dan industri tambang). Kebijakan moratorium ini bukan hanya di hutan alam dan gambut, tetapi juga harus memastikan mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial dan kawasan ekologi genting lainnya seperti kawasan ekosistem karst, mangrove dan pulau-pulau kecil, yang kini terancam oleh berbagai praktek industri ekstraktive berbasis lahan dan rakus air. WALHI merekomendasikan dan mendesak Presiden untuk memperpanjang dan memperkuat kebijakan moratorium dengan rentang waktu minimal 25 tahun bagi perizinan di semua sektor sumber daya alam seperti perkebunan sawit, kebun kayu, dan industri tambang dengan capaian yang jelas dan terukur. WALHI menilai jeda pemberian izin dalam kurun waktu minimal 25 tahun yang dalam periode pemerintahan artinya berada dalam 5 periode pemerintahan, merupakan waktu yang cukup untuk melakukan pembenahan tata kelola sumber daya alam Indonesia dan menyelesaikan konflik struktural sumber daya alam. Dalam kurun waktu minimal 25 tahun tersebut, harapannya cukup waktu bagi alam untuk memulihkan dirinya, memberikan hutan alam dan ekosistem rawa gambut dan kawasan ekosistem esensial lainnya untuk bernafas. Dalam kurun waktu minimal 25 tahun moratorium, pemerintah harus aktif melakukan tindakan yang jelas dan terukur untuk:
- Review Perizinan
- Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi
- Pengembalian, perlindungan dan pengakuan atas wilayah kelola rakyat
- Pemulihan kawasan ekosistem esensial yang telah mengalami pengrusakan untuk kepentingan industri ekstraktive dan industri berbasis lahan (hutan alam, rawa gambut, karst, mangrove dan pulau-pulau kecil)
Dalam kurun waktu minimal 25 tahun, WALHI mendorong langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap atau paralel, yakni sebagai berikut:
- Mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit dan sektor lainnya seperti HPH, HTI dan tambang dalam bentuk Peraturan Presiden.
- Memperkuat perlindungan hutan alam dan lahan gambut melalui audit perizinan seluruh industri/usaha berbasis lahan. Audit perizinan untuk melihat aspek pelanggaran hukum dan konflik. Dari hasil audit perizinan ini, akan diklasifikasikan pada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan dan penciutan wilayah konsesi korporasi, serta penyelesaian konflik
- Mempercepat pelaksanaan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pengelolaan tanah antara usaha skala besar dengan rakyat dan petani miskin. HGU perkebunan yang bermasalah dan atau telah habis masa izinnya, diambilalih oleh negara dan diredistribusikan kepada rakyat untuk dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- Mendorong ekosistem rawa gambut yang sudah mendapatkan izin usaha tetapi belum ada kegiatannya segera diambilalih oleh negara, sebagai langkah perlindungan dan penyelamatan ekosistem rawa gambut. Memastikan korporasi yang melakukan pengrusakan hutan alam, lahan gambut serta kawasan ekosistem esensial lainnya untuk melakukan pemulihan sebagai tanggung jawab mereka, tanpa mengurangi kewajiban hukumnya
- Melakukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia disertai dengan rencana aksi dan indikator capaian yang terukur, mencakup: (a)Membentuk Tim Independen untuk melakukan audit perizinan dan merekomedasikan pencabutan atau penciutan izin-izin perkebunan yang melanggar hukum, (b)Penguatan kerangka regulasi perkebunan kelapa sawit dan sinkronisasi dengan regulasi sektor lainnya (kehutanan, pertambangan, penataan ruang, dan lain-lain), serta (c) Melakukan upaya-upaya intensifikasi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada khususnya pekebunan skala kecil, inventarisasi kebun sawit non skema, dan penataan hilirisasi industri sawit.
Jika penguatan kebijakan moratorium dilakukan bersamaan dengan langkah-langkah aktif yang dilakukan oleh pemerintah selama minimal 25 tahun, negara dapat menyelamatkan hutan alam, ekosistem rawa gambut dan kawasan ekosistem esensial lainnya seperti karst dapat melampaui target Rencana Kerja Tahunan Kehutanan Nasional 69.144.073. Dari analisis spasial terhadap arahan RKTN dengan PIPIB, tersedia potensi sebesar sekitar 80 juta hektar wilayah yang terlindungi. Leadership dari Presiden menjadi kunci bagi pencapaian kebijakan moratorium, yakni perbaikan kebijakan dan pembenahan tata kelola kekayaan alam untuk menghentikan deforestasi dan degradasi lingkungan hidup serta penyelesaian konflik tenurial. [1] WALHI memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, semua hutan hujan di dataran rendah akan rusak apabila tidak segera diambil langkah-langkah perubahan radikal. Kayu tebangan tersebut dikonsumsi oleh industri-industri kehutanan yang rakus –seperti pabrik penebangan kayu, pabrik pulp dan kayu lapis serta manufaktur produk kayu. WALHI mengatakan bahwa pada tahun 2002, kebutuhan kayu dari industri penebangan kayu yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai angka sekitar 63 juta meter kubik. Tetapi, ijin yang diberikan pemerintah untuk penebangan kayu hanya mencapai 12 juta meter kubik. Jurang ini semakin melebar setiap tahunnya seiring meluasnya hutan-hutan yang terus dirusak. Artinya, kekurangan sebanyak 51 juta meter kubik didapat melalui sumber-sumber lain, yang sebagian besar bersifat ilegal.