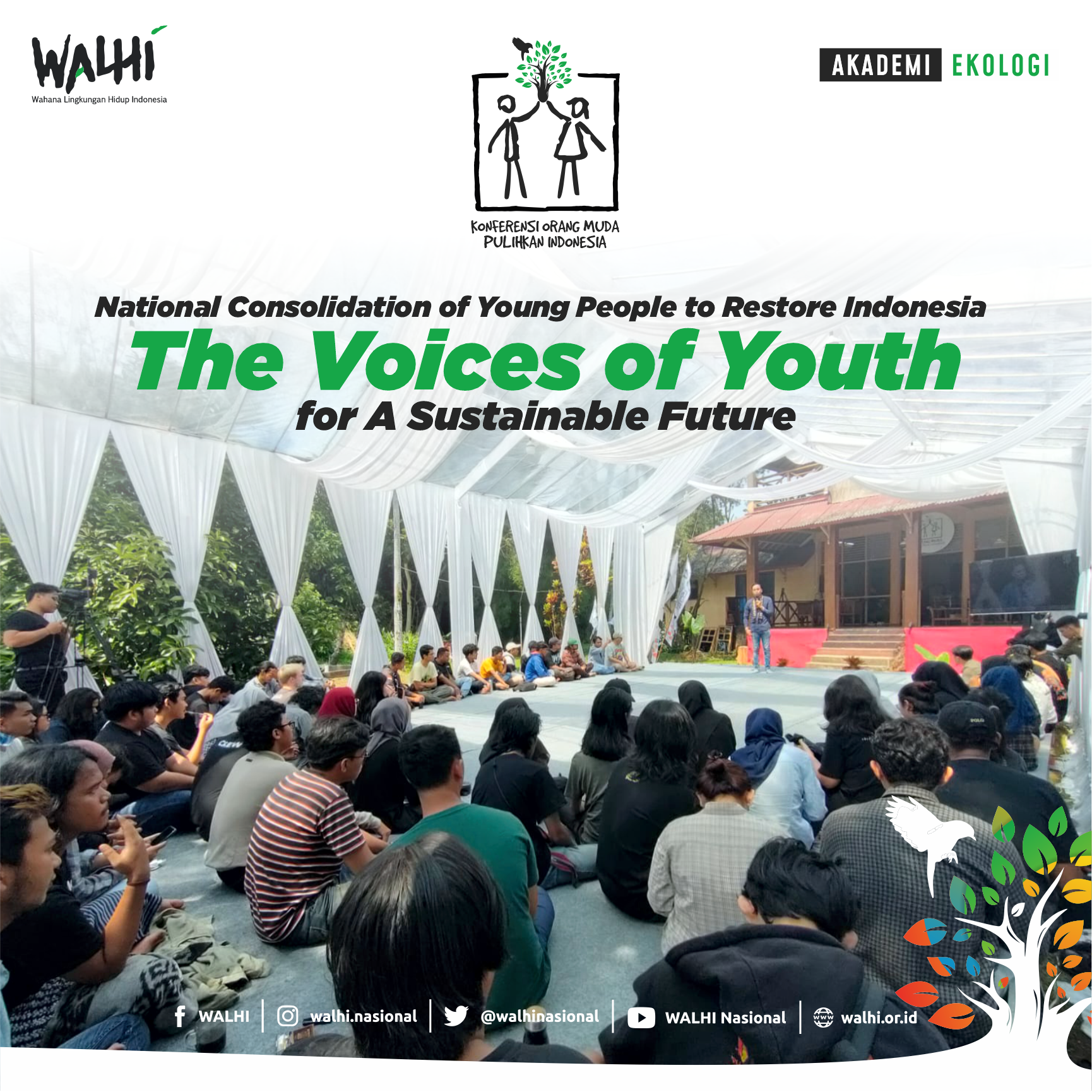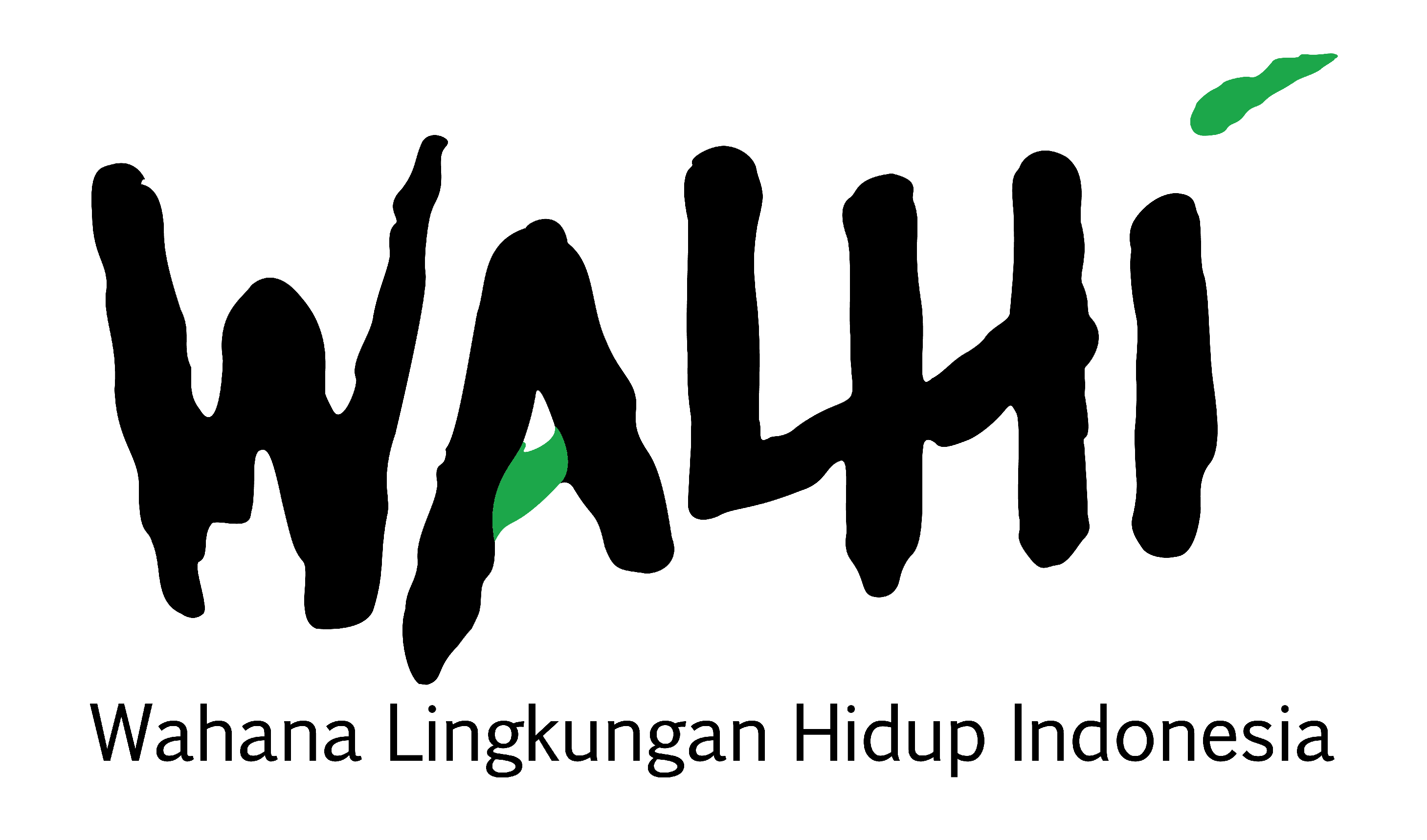Menyoal Kelangkaan Minyak Goreng Sawit
Uli Arta Siagian
“Tanah airku aman dan makmur. Pulau kelapa yang amat subur... Melambai-lambai… Nyiur di pantai…”
Begitu sebagian lirik lagu ‘Rayuan Pulau Kelapa’ karya Ismail Marzuki. Saat menulis lirik lagu ini, sang pencipta tentu tak lepas dari realitas betapa nusantara ini kaya dengan kelapa yang mengisi kejayaan perekonomian.
Abad 18, kelapa pernah jadi komoditas dagang utama. Kopra nusantara merajai pusat-pusat perdagangan komoditas dunia (Asba: 2007, Heersink: 1999 dikutip dalam Membunuh Indonesia). Kejayaan ini kemudian dihancurkan tipuan pengetahuan dan kampanye buruk bahwa minyak kelapa berbahaya bagi kesehatan karena menyebabkan kolesterol yang gencar disuarakan Amerika kala itu.
Pasca perang dunia kedua, ekspor minyak kelapa ke Amerika kembali meningkat, jauh melampaui penjualan minyak kedelai yang sedang mereka galakkan. Setidaknya sejak perang Asia Timur Raya, saat balatentara Jepang mengusasi Filipina dan wilayah Pasifik lain, aliran minyak kelapa terputus. Situasi itu, memaksa Amerika mengembangkan bahan minyak goreng lain terutama minyak kedelai.
Kala itu, muncul hasil penelitian kalau minyak jenuh seperti minyak kelapa meningkatkan kolesterol dalam darah hingga menyebabkan penyakit jantung. Temuan ini kemudian dimanfaatkan oleh American Soybean Association (ASA) untuk mengkampanyekan bahaya minyak kelapa dan mempromosikan minyak kedelai sebagai minyak paling sehat.
Sejak itu, Lembaga-lembaga di Amerika seperti Corn Product Company (CPC Internasional), Food and Drug Administration (FDA), Center For Science in the Public Interest (CSPI) dan American Heart Saver Association (AHSA) aktif membuat pendidikan-pendidikan tentang bahaya minyak kelapa.
Pada 1972, mereka mendorong aturan pemberian label peringatan “kaya akan lemak yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah” pada produk minyak kelapa.
Sampai 1988, kampanye buruk minyak kelapa terus mereka galakkan, bahkan kongres Amerika Serikat menghasilkan rancangan Undang-undang untuk membendung impor minyak kelapa dan minyak sawit. Intinya RUU itu mewajibkan, minyak eks daerah tropis dipasangi label yang berbunyi: “mengandung atau tidak mengandung gemuk jenuh” (saturated fat).
Pada 2003, WHO mengeluarkan maklumat ditemukan bukti meyakinkan bahwa konsumsi palmitic acid meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.
Sederetan kampanye miring minyak kelapa ini bukan hanya membuat citra minyak kelapa buruk di Amerika namun meluas hingga ke seluruh dunia, bahkan Indonesia. Alih-alih menepis kampanye buruk, otoritas Kesehatan dalam negeri justru mengamininya. Padahal, selama ribuan tahun masyarakat Indonesia mengkonsumsi minyak kelapa.
Akhirnya, para petani di wilayah-wilayah sentra kelapa di nusantara seperti di Sulawesi, Sumatera dan Jawa, harus menanggung kebangkrutan dari kampanye ini. Bahkan, hingga sekarang, lidah banyak orang Indonesia jadi asing dengan minyak kelapa.
Historis matinya industri kelapa rakyat ini sebelumnya ditulis dalam buku “Membunuh Indonesia.” Bukan hanya kelapa, beberapa komoditas lain seperti garam, gula, dan jamu juga mengalami nasib sama.
Infrastruktur memperkuat perkebunan sawit
Seiring runtuhnya industri minyak kelapa rakyat, Pemerintah Indonesia justru melihat peluang lain, yaitu minyak sawit. Bagunan suprastruktur dan infrastruktur melalui kebijakan dan produk hukum yang mengakomodasi perluasan ekspansi izin sawit dilakukan pengurus negara. Ditambah permintaan ekspor dari negara-negara luar yang terus meningkat, membuat sawit melejit pesat.
Pada 1912, sawit diusahakan sebagai tanaman komersial dan ekspor CPO pertama sekali Indonesia pada 1919. Saat itu perkebunan-perkebunan sawit skala besar dimiliki oleh pemerintahan Belanda. Pada 1957, Presiden Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.
Jatuhnya rezim Soekarno berganti Soeharto membuka lebar keran investasi. UU Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) diikuti UU sektoral lain seperti UU Nomor 5/1967 tentang Kehutanan. Sejak ada UU Kehutanan tahun 1967, pemberian izin usaha di sektor kehutanan seperti izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (HPH) dan izin usaha pemanfataan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (HTI) begitu masif. Ia jadi pintu perusakan hutan Sumatera dan Kalimantan.
Eks-eks konsesi kehutanan itu berganti jadi perkebunan-perkebunan sawit. Setidaknya, pada 1980-an, Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagai perusahaan swasta untuk merambah bisnis sawit melalui program perkebunan besar swasta nasional (PBSN).
Program perkebunan inti rakyat (PIR) pun digalakkan, ditambah lagi dengan pengintegerasian PIR dengan program transmigrasi (PIR-Trans). Dengan begitu, sawit skala besar milik perusahaan-perusahaan besar makin luas.
Pada 1980, luas sawit di Indonesia 200.000 hektar, hampir semua warisan Belanda. Hingga 2009, luas kebun sawit mencapai 7,2 juta hektar. Seiring perkebunan sawit meluas, pembangunan infrastruktur seperti pabrik-pabrik minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga terus bertambah. Lagi-lagi, pabrik-pabrik CPO pun didominasi oleh perusahaan swasta.
Sampai 2021, lusan sawit mencapai 14,9 juta hektar. Ekspansi sawit bisa makin tinggi seiring muncul UU Cipta Kerja yang saat ini inkonstitusional bersyarat. Investasi adalah ruh dari UU ini. Kebijakan lain, seperti pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) dengan fokus sumber sawit.
Komoditas global
Ekspansi sawit tak lepas dari permintaan global, salah satu Uni Eropa. Sejak pemberlakuan renewable energy directive pada 2008, konsumsi sawit untuk biodiesel di Uni Eropa meningkat secara signifikan. Konsumsi ini dipenuhi melalui impor minyak sawit dan Indonesia jadi pengekspor minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan itu.
Setidaknya pada 2018, Uni Eropa mengkonsumsi 53% dari semua minyak sawit impor untuk biodisesel, selain itu 12% dari impor minyak sawit digunakan untuk pemanas dan listrik. Berarti, 65% dari impor minyak sawit dibakar untuk jadi biofuel, sisanya, untuk pangan dan keperluan industry olekimia (Transport and Environment, 2019).
Kebijakan renewable energy di Uni Eropa yang mewajibkan seluruh negara-negara yang jadi bagian Uni Eropa untuk meningkatkan penggunaan energi terbaharukan.
Faktanya, menstimulus ekpansi perkebunan sawit di Indonesia, yang pada akhirnya ekspansi ini mengorbankan banyak sekali jiwa rakyat Indonesia, hutan-hutan Indonesia, lingkungan hidup dan satwa-satwa yang dilindungi.
Bukan hanya memenuhi konsusmsi Uni Eropa, Indonesia juga memenuhi konsumsi negara-negara di benua lain seperti Asia, Afrika, Australia dan Amerika.
Dari rangkaian kebijakan dan produk-produk hukum yang mengakomodasi perluasan izin sawit, membuat Indonesia jadi penghasil sawit terbesar di dunia. Dengan luasan sawit yang mencapai 14,9 juta hektar hingga 2021, 60% atau seluas 9 juta hektar perkebunan sawit adalah milik perkebunan besar swasta.
Dalam Studi Kuasa Taipan Sawit di Indonesia yang disusun oleh TuK Indonesia, 9 juta hektar perekebunan sawit ini dikuasai 25 grup perusahaan sawit, yang dikendali 29 keluarga kaya raya.
Dari 25 grup perusahaan itu hanya lima grup memegang kendali penting dalam luasan wilayah tanam. Dengan memegang kendali penting atas luasan wilayah tanam, mereka juga memegang kendali atas pabrik-pabrik minyak sawit. Termasuk, memegang kendali produksi minyak goreng.
Beberapa merek minyak goreng kemasan yang kini digunakan seperti Filma, Mitra, Kunci Mas adalah milik Sinar Mas Group. Sania, Siip, Sovia, Fortune, Camilla, Mahkota adalah milik Wilmar Group. Bimoli, Delima dan Happy adalah merek minyak goreng milik Salim Group.
Kepemilikan lahan yang ditanami sawit antara perusahaan dan rakyat sangat timpang. Sekitar 2,74 juta keluarga petani hanya menguasai 5 juta hektar sawit rakyat (BPS: 2019).
Meskipun kalau diperiksa secara faktual, kebun-kebun rakyat yang disebutkan BPS juga di lapangan sebagian besar dikuasai tuan-tuan tanah kecil yang juga merupakan elit-elit politik, elit-elit pemerintahan di daerah-daerah, dan pemodal lain.
Belum lagi, tidak sedikit kebun-kebun sawit milik rakyat ini jalan dengan skema kemitraan plasma, seperti kebun kas desa, kebun masyarakat desa, dan pola kemitraan plasma lain dengan nama-nama berbeda.
Juga hasil tandan buah segar dari kebun-kebun sawit milik rakyat dijual ke pabrik-pabrik milik perusahaan yang juga dimiliki 25 grup besar. Artinya, industri sawit Indonesia dikuasai dan dikendalikan pemodal yang hanya segelintir orang.
Kelangkaan minyak goreng sawit di pasaran hanya sebagian kecil persoalan yang harus ditanggung di balik perkebunan sawit yang makin meluas. Persoalan mendasarnya, corak ekonomi kapitalistik, dengan konsekuensi besar adalah penguasaan besar-besaran sumber daya alam oleh para pemodal yang dilegitimasi melalui kebijakan dan aturan-aturan hukum.
Konsekuensi ikutan lain adalah perampasan wilayah kelola rakyat (WKR), konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan, dan kualitas lingkungan hidup menurun drastis serta pelanggaran HAM maupun deforestasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, 3,4 juta hektar sawit illegal dalam kawasan hutan. Perubahan bentang hutan menjadi perkebunan monokultur sawit dalam skala besar ini menyebabkan fungsi hutan sebagai penata air hilang. Banjir dan longsor makin sering melanda kala musim penghujan.
Saat kemarau, krisis air bersih juga terjadi dimana-mana, dan kebakaran hutan maupun lahan terus terjadi setiap tahun. Sejak 2016-2021, seluas 3,4 juta hutan dan lahan gambut terbakar. Kebakaran hutan dan lahan ini berada di konsesi-konsesi perizinan kehutanan maupun perkebunan sawit perusahaan. Sangat besar kerugian dampak kebakaran ini harus ditanggung rakyat dan negara.
Bukan hanya kerugian material, juga non material seperti penyakit asma, anak-anak tidak bisa bersekolah dan bermain, serta ingatan buruk lain mengenai suramnya keseharian dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Asap ini bahkan merugikan dan mengganggu warga negara lain, seperti Malaysia dan Singapura.
Saat krisis air, banjir dan longsor, perempuan adalah entitas paling menanggung beban. Air sebagai kebutuhan essensial manusia, perlu setiap hari dari keperluan mandi, memasak, sampai mencuci. Semua pekerjaan itu lekat dengan keseharian perempuan. Ketika air tidak ada, pekerjaan makin berat ditanggung perempuan. Mereka akan mencari air ke sumber yang relatif jauh dari rumah, atau membeli air bagi yang mampu.
Ekspansi masif sawit juga meningkatkan konflik di kampung-kampung. Perampasan tanah, kriminalisasi, kekerasan, intimidasi terus terjadi di kampung-kampung. Konflik yang berlangsung lama, antara rakyat dan korporasi belum selesai, yang baru pun muncul.
Walhi mencatat, sepanjang 2021 setidaknya 58 kasus kriminalisasi, 34% kasus di sektor perkebunan dan kehutanan.
Kehidupan rakyat yang jadi buruh di perkebunan sawit juga buruk. Pelanggaran HAM buruh perempuan dan laki-laki kerap kali terjadi. Upah buruh harian tidak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Bahkan, untuk mengejar target harian, buruh harus mengajak anak ataupun anggota keluarga yang lain untuk bekerja di perkebunan tanpa bayaran.
Mereka ada ada kelengkapan bekerja. Buruh perempuan memupuk, menyemprot hama tanaman, tidak diberi alat pelindung lengkap. Padahal, zat-zat kimia dari pupuk, dan desinfektan hama sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan. Bahkan, beberapa studi di beberapa wilayah terjadi pemerkosaan buruh perempuan di perusahaan sawit.
Lindungi wilayah rakyat
Sudah terlalu banyak yang diambil, pun beban berat yang harus ditanggung rakyat membuktikan, negara salah mengurus sumber-sumber penghidupan. Sekarang, saatnya negara mengakui kegagalan dengan mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat.
Dalam wilayah kelola rakyat terdapat keberagaman, kolektifitas, praktik-praktik arif dalam mengelolah sumber-sumber penghidupan, dan kekuatan ekonomi yang terbukti memiliki resiliensi tinggi. Walhi melakukan studi ekonomi yang selanjutnya disebut sebagai ekonomi nusantara di beberapa wilayah kelola akyat di lima landskap. Yaitu, gambut, hutan daratan tinggi, perbukitan Sumatera, hutan dataran rendah dan pesisir.
Ekonomi nusantara di wilayah kelola rakyat ini memiliki empat nilai pengikat, pertama, hubungan sejarah, kedua, hubungan dengan lanskap ekologis, dan ketiga, praktik ekonomi tidak destruktif. Keempat, memiliki dimensi pemulihan kondisi sosial-ekologis.
Studi ini menyebutkan, pada satu desa obyek studi, tidak kurang dari miliaran uang berputar dari hasil keberagaman produk masyarakat desa.
Seharusnya, ekonomi nusantara yang terbangun dalam wilayah kelola rakyat ini menjadi kekuatan bangsa hingga pengakuan dan perlindungan jadi hal paling penting dan mendasar yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu suprastruktur dan infrastruktur untuk memperkuat ekonomi rakyat ini.
Uli Arta Siagian
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional