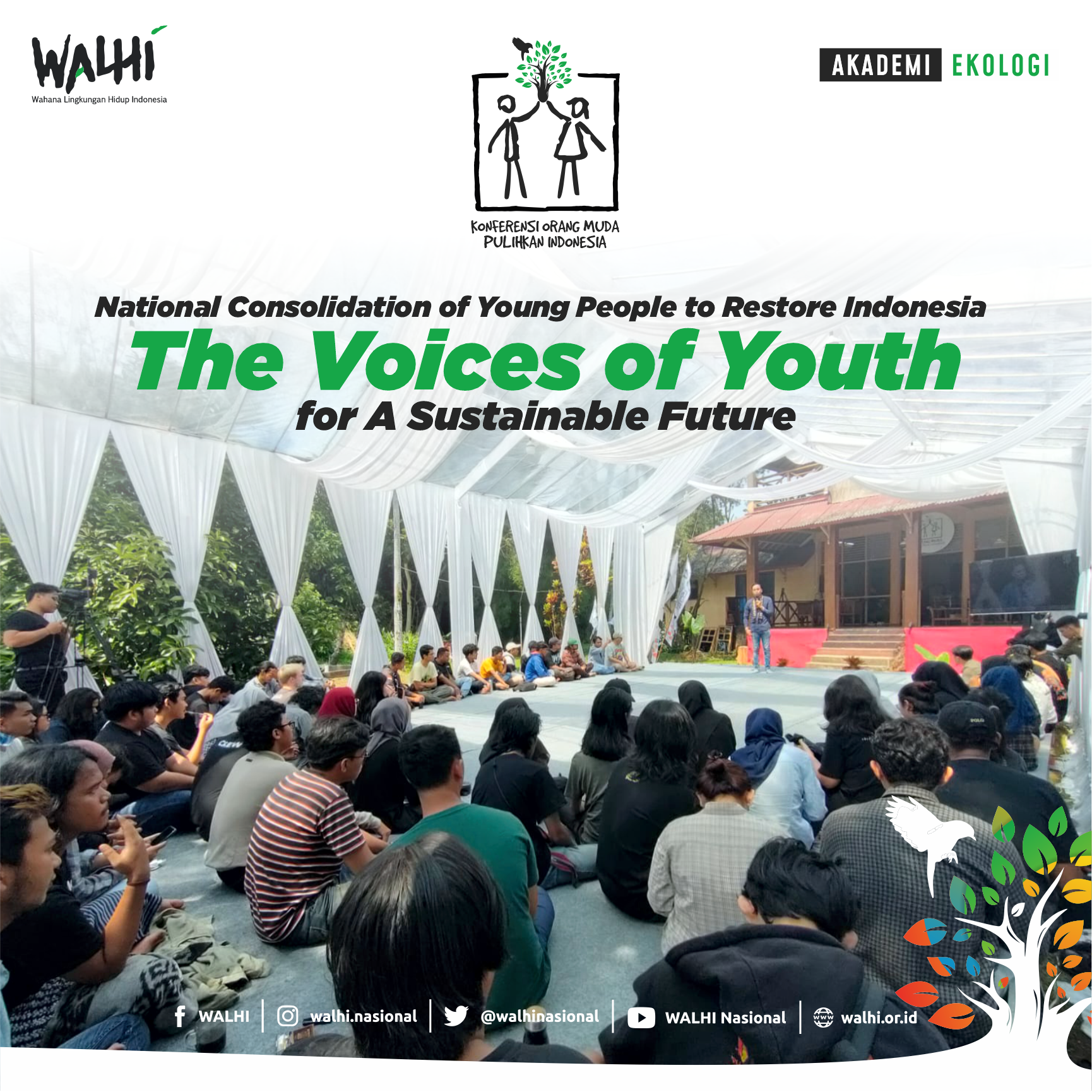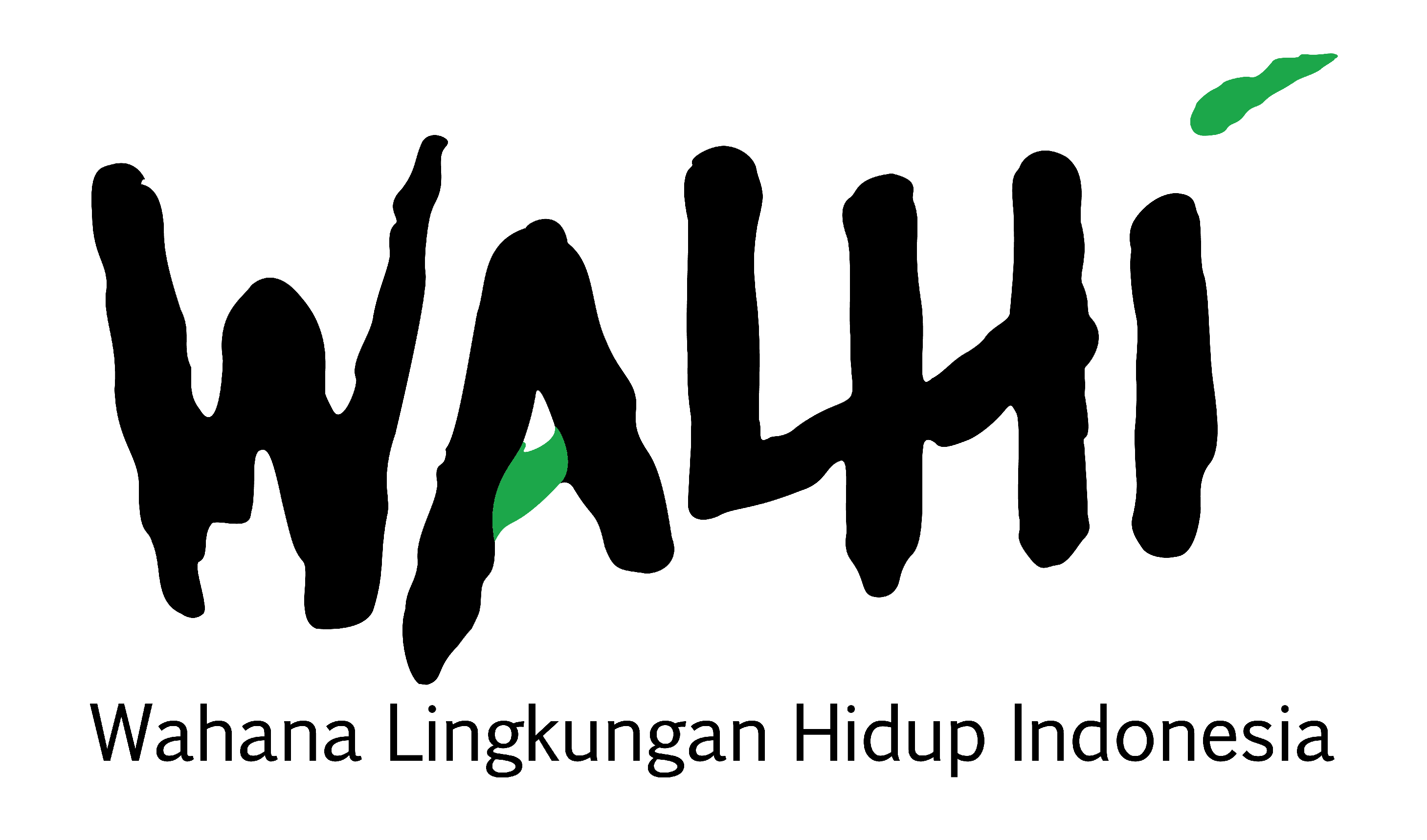Pernyataan Sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Hari ini 12 Desember 2020 kita memperingati lima tahun Perjanjian Paris. Perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim ini diadopsi oleh 196 pihak pada COP21 di Paris pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016. Indonesia sebagai salah satu pihak yang menandatangani Perjanjian Paris telah meratifikasi dalam hukum nasional melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Dalam Perjanjian Paris, semua pihak dengan mempertimbangkan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities, diharuskan membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri.
Target untuk menahan kenaikan rata-rata suhu bumi tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celcius adalah juga desakan dari masyarakat sipil dan gerakan sosial yang tergabung dalam gerakan keadilan iklim. Keadilan iklim disebut dalam pembukaan Perjanjian Paris yang menyatakan bahwa aksi kebijakan dan proyek untuk melawan perubahan iklim harus memegang prinsip keadilan iklim. Prinsip tersebut tertuang secara rinci dalam dokumen Prinsip-prinsip Bali untuk keadilan Iklim atau Bali Principles for Climate Justice yang disusun pada tahun 2002 oleh organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial dari berbagai negara.
Lima tahun sejak Perjanjian Paris disepakati, konsentrasi gas rumah kaca terutama dari penggunaan energi fosil belum menunjukkan tren mencapai puncaknya dan kemudian menurun. Dari tahun 1990-2019 emisi dari penggunaan energi fosil mencapai 38 Gt CO2, naik rata-rata 0,9% pertahun antara tahun 2010-2019. Pada tahun 2020, emisi dari penggunaan energi fosil tersebut turun sebesar 7% dari jumlah emisi tahun 2019, karena faktor pandemi dan perlambatan ekonomi global. Meski demikian secara umum emisi gas rumah kaca belum menunjukkan akan mencapai puncak dan konsisten menurun setelahnya. Disisi lain, komitmen dari para pihak melalui Komitmen Kontribusi Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) belum cukup ambisius menahan suhu bumi dibawah 1,5 derajat celcius, justru Komitmen Kontribusi Nasional dari seluruh negara termasuk Indonesia akan mengarah pada meningkatnya suhu bumi mencapai 3-4 derajat celcius.
Sains terbaru seperti tertuang dalam Laporan Khusus Lembaga Panel Ahli Antarpemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) tahun 2018, menunjukkan target 2 derajat celsius tidak cukup menghindari bencana iklim. Perbedaan 0,5 derajat celcius berdampak signifikan, jika melewati ambang batas 1,5 derajat celcius dibandingkan dengan 2 derajat celcius. Perbedaan 0,5 derajat celcius menyebabkan konsekuensi fatal bagi penduduk bumi dan ekosistem. Dampak tersebut akan lebih parah dirasakan oleh negara-negara di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim dan kenaikan muka air laut, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan puluhan juta orang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil, risiko tersebut menjadi berlipat ganda. Proyeksi dari Climate Centralmenyebutkan bahwa, setidaknya 23 juta orang di Indonesia akan terdampak langsung dan dipaksa menjadi pengungsi internal jika kenaikan muka air laut mencapai 0,6-2 meter di akhir abad.
Di tahun ini, fenomena tersebut sudah dialami oleh komunitas di garis depan yang terdampak krisis iklim, seperti di Pulau pari, Kepulauan Seribu, yang dihantam banjir rob dua kali tahun ini, sesuatu yang belum pernah terjadi selama 65 tahun terakhir. Komunitas nelayan di pesisir Nambangan dan Cumpat, Surabaya yang dihantam “angin timur pamitan” yang menyebabkan gelombang tinggi dan banjir rob serta merusak puluhan kapal nelayan. Desa Matawai Atu, di pesisir Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur yang tergerus abrasi hingga 100 meter. Pada awal 2020, WALHI Sumatera Selatan melaporkan bahwa Pulau Betet dan Pulau Gundul, di Kabupaten Banyuasin telah tenggelam, masing-masing 1 dan 3 meter di bawah permukaan air laut. Ini hanya sebagian kecil potret kerentanan dan dampak iklim pada komunitas di garis depan.
Sayangnya, hingga saat ini, jika dilihat dari dokumen NDC Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebijakan iklim Indonesia masih tidak ambisius dan serius baik dari target, aksi mitigasi maupun adaptasi. Kebijakan iklim Indonesia juga tidak melihat aspek loss and damage atau kerugian dan kerusakan akibat bencana iklim dan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan tersebut. Setidaknya ada lima hal, mengapa kebijakan iklim Indonesia tidak ambisius dan serius.
Pertama, kebijakan iklim Indonesia tidak merefleksikan sains terbaru, terutama mengacu pada laporan khusus IPCC tahun 2018 tentang perubahan iklim dan target 1,5 derajat celcius. Komitmen iklim Indonesia adalah 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional. Komitmen penurunan emisi ini dibandingkan dengan skenario tanpa intervensi atau business as usual (BAU). Komitmen tersebut tidak cukup untuk berkontribusi secara global menahan suhu bumi tidak melewati 1,5 derajat celcius. Apalagi komitmen penurunan tersebut didasarkan pada BAU sebagai pembanding bukan pada emisi tahun tertentu. Selain itu dengan menggunakan konsep anggaran karbon (carbon budget) atau emisi yang masih diperbolehkan, dengan menghitung anggaran karbon yang adil bagi Indonesia dengan mempertimbangkan tren emisi tahunan dan menghitung emisi historis, maka anggaran karbon Indonesia akan habis pada tahun 2027.
Kedua, kebijakan iklim Indonesia bertumpu sebagian besar pada sektor berbasis lahan, seperti kehutanan, lahan gambut, pertanian dan alih fungsi lahan. Beban penurunan emisi sektor energi dibiarkan longgar meski tren sepuluh tahun kedepan, sektor energi akan menjadi sumber emisi terbesar Indonesia melampaui sektor berbasis lahan. Sumber energi fosil masih menjadi tumpuan pemenuhan energi nasional, sekaligus menjadi pundi-pundi pendapatan ekspor nasional. Ekspor Indonesia masih tergantung pada ekstraksi sumber energi kotor, tidak jauh berbeda dengan masa lalu. Agenda untuk mentransformasi ekonomi tidak lagi tergantung pada ekspor komoditas yang menghancurkan lingkungan dan memperparah krisis iklim hanya isapan jempol ditengah semakin menguatnya keberpihakan pemerintah pada pelaku industri kotor ini. Ekonomi (ekstraktif) masih menjadi panglima.
Ketiga, Aksi mitigasi perubahan iklim Indonesia didominasi solusi palsu yang tidak menjawab akar persoalan dan melanggengkan praktek business as usual serta menghindari aksi iklim yang lebih ambisius. Hal itu terjadi di semua sektor baik di sektor berbasis lahan, energi dan sampah. Solusi palsu seperti mengganti ketergantungan minyak bumi dengan biofuel dari sawit adalah salah satunya, meski diklaim oleh pemerintah dapat mengurangi emisi dari sektor energi, perluasan kebun sawit akan memperparah emisi di sektor berbasis lahan karena penggundulan hutan, pembakaran gambut dan penggunaan input kimia yang berlebihan. Dalih hilirisasi batubara juga menunjukkan hal serupa, alih-alih menyiapkan peta jalan transisi energi yang berkeadilan dengan meninggalkan batubara, pemerintah memilih jalan mentransformasi industri tambang batubara menjadi bentuk energi fosil lainnya melalui gasifikasi. Di sektor kehutanan, penerapan bioenergi dari Hutan Tanaman Industri untuk energi adalah satu dari sekian solusi palsu di sektor ini, termasuk rencana Co-Firing PLTU batubara dengan biomassa baik dari kayu maupun sampah. Selain itu, tumpuan pendanaan yang menggantungkan pada dagang karbon dan offset hanya akan menguntungkan pedagang karbon, korporasi dan negara maju untuk mengelak dari tanggung jawab penurunan emisi yang lebih drastis. Solusi palsu ini hanya akan memperburuk perampasan tanah dan wilayah kelola rakyat dan mengancam penghidupan masyarakat adat, dan mereka hidup bergantung pada hutan.
Keempat, kontradiksi kebijakan iklim dengan kebijakan terbaru seperti revisi UU Minerba dan UU yang inkonstitusional seperti UU Cipta kerja serta peraturan lain yang memperbolehkan eksploitasi lahan gambut, alih fungsi hutan lindung untuk food estate, menunjukkan komitmen iklim pemerintah Indonesia tidak termanifestasi dalam kebijakan lintas sektor yang selaras. Kebijakan iklim dipandang sebagai kebijakan yang terpisah dan hanya menjadi bahan diplomasi internasional, tanpa serius diintegrasikan dengan kebijakan lintas sektoral. Hal ini bertolak belakang dengan negara lain, dimana kebijakan iklim suatu negara akan berpengaruh pada urusan ekonomi dan juga perdagangan. Mitra dagang Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa telah membuat komitmen untuk netral emisi dalam beberapa puluh tahun mendatang. Bahkan baru-baru ini Amerika Serikat yang sebelumnya menyatakan keluar dari Perjanjian Paris, dengan terpilihnya Presiden AS yang baru, menimbang untuk bergabung kembali dan berkomitmen untuk netral emisi. Republik Rakyat Cina-mitra dagang bilateral terbesar Indonesia-, yang dalam kategori UNFCCC tidak termasuk negara Annex I, seperti Indonesia, juga sudah menentukan netral emisi di tahun 2060. Sementara Indonesia masih belum punya strategi jangka panjang terkait kebijakan iklim yang justru diperparah dengan UU Cipta Kerja. Parahnya, perencanaan tata ruang baik darat (RTRW) dan laut (RZWP3K) semakin mengakomodasi kepentingan investasi ekstraktif dan destruktif yang beremisi tinggi.
Kelima, Kebijakan iklim Indonesia tidak berorientasi pada pemenuhan hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta tidak mencerminkan keadilan antargenerasi sebagaimana amanat pasal 28H ayat (1) UUD 1945, pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak Atas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang semestinya dapat dilaksanakan dalam bentuk hak warga negara untuk mengambil bagian peran serta, hak banding dan persetujuan dalam setiap kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup. Namun sayangnya, negara belum menjalankan kewajiban memenuhi, melindungi dan menghargai hak atas lingkungan hidup warga. Kebijakan iklim Indonesia juga masih menempatkan generasi muda sekedar objek dari kebijakan tanpa mempertimbangkan aspirasi mereka dan generasi mendatang. Jika situasi ketidakadilan baik intragenerasi maupun antargenerasi terus dibiarkan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi 68 % penduduk usia produktif hanya akan menjadi sekedar imajinasi. Generasi mendatang hanya akan mewarisi kerusakan bentang alam mulai dari Sumatera hingga Papua, mulai dari lanskap pesisir, pulau kecil hingga pegunungan. Selesai
Jakarta, 12 Desember 2020
Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Narahubung: Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim
harmono[at]walhi.or.id I +6281385072648
Catatan:
Prinsip-prinsip Bali untuk keadilan iklim bisa dilihat disini:https://corpwatch.org/article/bali-principles-climate-justice
Analisis kebijakan iklim Indonesia dalam perspektif keadilan antargenerasi dan rekomendasi kebijakan iklim lebih ambisius bisa dilihat disini https://www.walhi.or.id/desk-study-walhi-analisis-kesenjangan-kebijakan-iklim-indonesia-dalam-perspektif-keadilan-antargenerasi
Briefing paper WALHI terhadap NDC Indonesia di sektor energi bisa dilihat disini https://www.walhi.or.id/mendesak-transisi-energi-bersih-berkeadilan-dan-berdaulat-untuk-mewujudkan-keadilan-iklim
Kertas posisi WALHI dan FOE Eropa tentang isu sawit dalam perundingan perdagangan bebas, bisa dilihat disini https://www.foeeurope.org/no-palm-oil-eu-indonesia-deal-120319
Desakan WALHI untuk pembatalan Permen LHK Nomor 24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk food estate bisa dilihat disini https://www.walhi.or.id/stop-food-estate-di-kawasan-hutan-batalkan-peraturan-menteri-lhk-p-24-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-food-estate
Kertas Posisi WALHI atas RUU Ciptas Kerja bisa dilihat disini