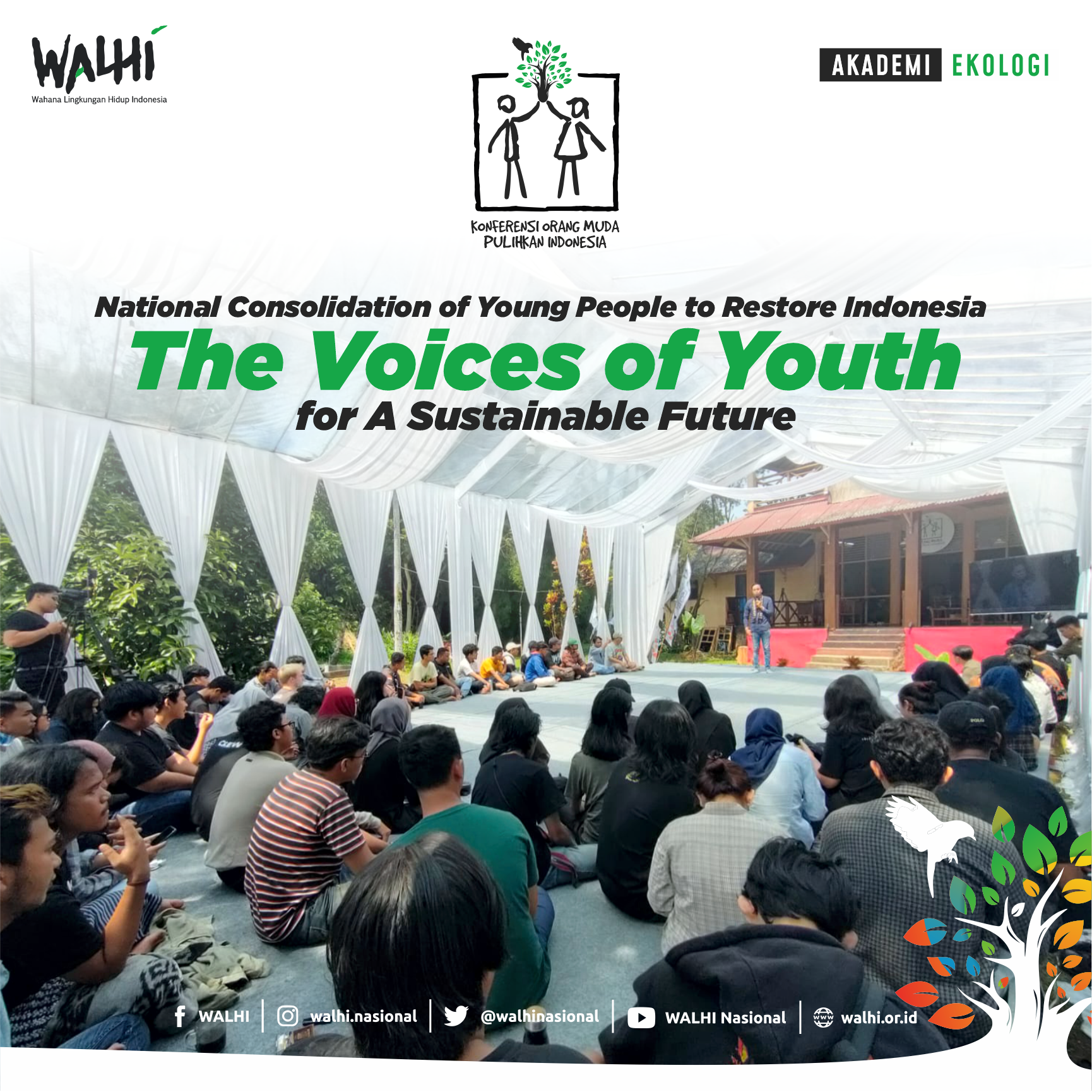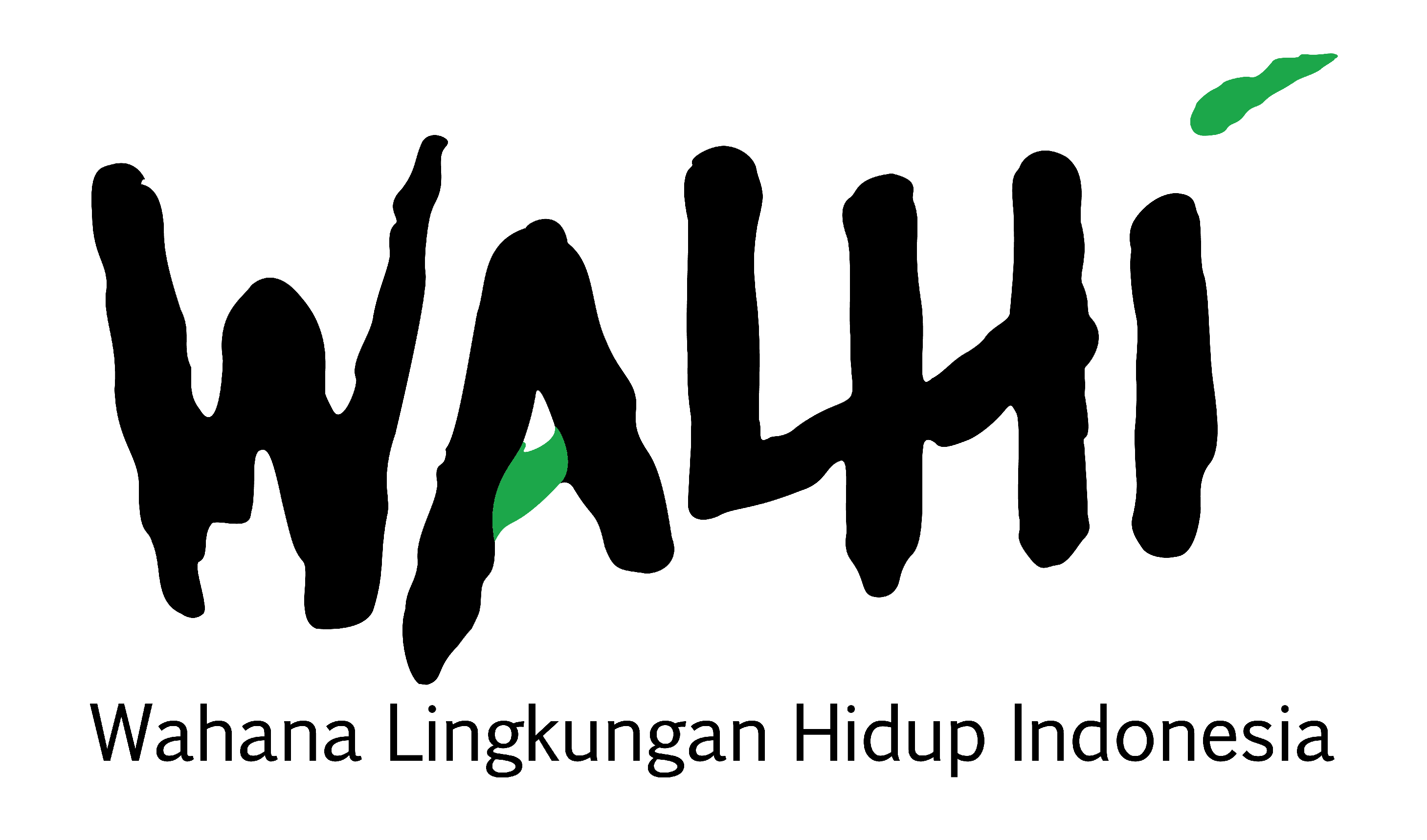..memaksakan Tambang di kawasan CAT Watu Putih mengancam kedaulatan pangan bukan hanya di Rembang, tetapi juga Blora dan Tuban.. Ungkapan diatas mungkin buat beberapa kelompok dianggap berlebihan, namun seringkali kita melihat persoalan pangan dari sisi akses (Jarak dan harga) dan ketersediaan saja. Faktanya pangan dan kelestarian lingkungan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Mencermati Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)[1] pada kawasan Cekungan Air Tanah Watu Putih di Kabupaten Rembang, ditemukan fakta bahwa sebagian besar kelelawar yang ditemukan pada riset KLHS tersebut merupakan pemakan serangga yang berperan dalam pengendalian hama pertanian di wilayah sekitarnya, dengan daya jangkau antara 5-10 km (hitungan minimum, beberapa jenis kelelawar mencapai daya jangkau hingga 41km) yang setara dengan 15.443. Ha. Jika jasa lingkungan yang selama ini perannya digantikan oleh pestisida, maka setidaknya akan ada penambahan biaya pestisida dalambiaya setahun senilai Rp 8.791.000.000,00 . Hal tersebut belum mempertimbangkan dampak dan biaya kesehatan yang keluar karena penggunaan pestisida, penurunan hasil panen karena kehilangan penyerbuk alami dari kelelawar, dan juga hilangnya hak atas air.
Indonesia memiliki kerawanan pangan tinggi setinggi, setidaknya dipengaruhi tiga hal besar: Pertama, Tingginya angka deforestasi akibat industri ekstraktif, perkebunan monokultur dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan lingkungan. Tingginya laju industri ekstraktif dan perkebunan monokultur secara langsung atau tidak berdampak pada penyusutan lahan pangan, memang sudah ada kebijakan moratorium yang beberapa saat lalu diperpanjang (hanya) dua tahun lagi, namun kebijakan tersebut belum bisa ditegakkan dengan tegas, diindikasikan dengan adanya titik api yang sebagian besar berada pada di wilayah konsesi perusahaan, bahkan di area Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)[2]. Kerawanan pangan bukan hanya terjadi di darat, pada proyek reklamasi teluk jakarta Kerugian nelayan akibat reklamasi mengalami penurunan pendapatan perbulan hingga mencapi 76%[3]. Kedua, Berada pada wilayah rawan bencana, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia, dimana bencana alam merupakan faktor utama kerawanan pangan transien di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), terdapat enam negara (Indonesia, Cina, Amerika Serikat, Filipina, Afganistan dan India) yang paling sering mengalami bencana alam. Hal lain yang mempengaruhi ialah cara pandang bahan pangan pokok yang disimplifikasi hanya pada beras saja, kebijakan pencetakan sawah baru secara masif dan melibatakan korporasi serta militer justru menimbulkan konflik lahan baru seperti di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Tidak ada upaya serius memahami pengetahuan lokal sebagai solusi, khususnya dalam budaya pangan. Ketiga, menerima dampak perubahan iklim. Perubahan iklim (yang juga dipengaruhi laju deforestasi) sangat berpengaruh terhadap kondisi pangan di Indonesia. Terjadinya kejadian iklim ekstrim yang menyebabkan hilangnya produksi tanaman pangan dalam jumlah yang signifikan sebagian besar berkaitan dengan fenomena El Niño/Southern Oscillation (ENSO). Peningkatan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celcius memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap curah hujan. Analisis mengenai dampak perubahan iklim terhadap produksi padi di Jawa menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun 2025 dan 2050, masing-masing akan berkurang sebesar 1,8 juta ton dan 3,6 juta ton dibandingkan tingkat produksi padi saat ini.[4]
Proses Industrialisasi dan ketergantungan hanya pada pangan tertentu saja, terjadi secara sistematis selama 4 dekade terakhir menghilangkan pengetahuan lokal dan kemampuan mitigasi terhadap perubahan iklim. Apa yang harus dilakukan? Dalam banyak pengalaman komunitas, pengetahuan lokal justru lebih mampu menjaga kedaulatan pangannya, hal tersebut ditunjukkan dengan Kemampuan bertahan benih lokal, pemahaman terhadap perilaku alam, serta kemampuan mitigasi yang bersumber dari pengetahuan lokal lebih mungkin diimplementasikan, sayangnya ekspansi industri ekstraktif, serta kebijakan yang tidak berpihak membuat masyarakat tersingkir, maka Pengembalian, perlindungan dan Pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat menjadi hal yang mendesak. Pada sisi lain harus ada upaya menekan laju ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan besar monokultur yang berdampak pada degradasi lahan pangan. Harus ada review izin menyeluruh terhadap industri ekstraktif, begitu juga dengan kebijakan moratorium, seharusnya bersifat mandatory, bukan hanya bagi kementerian / lembaga negara lainnya, tetapi termasuk bagi pemerintah daerah yang kewenangannya kini kembali bertumpu di pemerintah Provinsi sesuai UU 23/2014. [1] Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan; Tahap 1; Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih & Sekitarnya, Kabupaten Rembang [2] Siaran Pers WALHI 12 Mei 2017 : “Moratorium 25 tahun Menghentikan Deforestasi dan Menyelesaikan Konflik” [3] Data : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DHI WATER, BOTH ENDS; Riset “Social Justice at bay” oleh Both Ends, SOMO, tni. [4] Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan Indonesia 2015 ; Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian and World Food Programme (WFP)